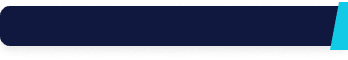Cakupan Cuci Darah Mandiri di Indonesia Masih Rendah

Cakupan Cuci Darah Mandiri di Indonesia Masih Rendah
A
A
A
HASIL beberapa kajian menunjukkan bahwa CAPD atau peritoneal dialisis sebenarnya lebih praktis dan efektif dibanding HD sebagai terapi gagal ginjal kronik (GGK). Masalahnya, penggunaan CAPD belum begitu populer. Apa sebabnya?
Komplikasi penyakit ginjal kronik tidak hanya butuh biaya perawatan mahal, tetapi juga risiko kematian tinggi. Terapi GGK meliputi transplantasi ginjal, hemodialisis (HD), dan continous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) atau sering disebut peritoneal dialisis saja. Metode peritoneal dialisis yaitu pasien melakukan cuci darah secara mandiri dan tidak perlu ke rumah sakit.
Prof Budi Hidayat, Ketua CHEPS FKMI UI, mengatakan, data antara Januari 2014-Desember 2015 menunjukkan, jumlah pasien penyakit ginjal tahap akhir mencapai lebih dari 5 juta (4,5 juta rawat jalan dan lebih dari 600.000 rawat inap). Total klaim biaya perawatan HD mencapai Rp7,6 triliun sejak awal BPJS (2014) sampai 2016. Hasil beberapa kajian menunjukkan bahwa biaya CAPD sebenarnya lebih efektif dibandingkan HD. Selain itu, kualitas hidup pasien yang menjalani CAPD umumnya lebih baik dan tidak membutuhkan klinik atau sarana khusus.
"Tetapi, faktanya berbeda. Di Indonesia, baru 2% pasien gagal ginjal yang sudah menggunakan CAPD (data tahun 2016)," ungkap Prof Budi.
Data BPJS Januari-Desember 2016 menunjukkan bahwa baru 18.597 peserta CAPD dengan total biaya Rp98,7 miliar, jauh dibandingkan pasien HD yang mencapai 3,1 juta orang dengan total biaya Rp3,1 triliun. Mengapa CAPD kurang populer?
Untuk menjawabnya dapat dilihat fenomena terapi dialisis sejak BPJS dijalankan. Salah satu respons paling signifikan dari diberlakukannya BPJS adalah berkembangnya klinik HD di seluruh Indonesia. Tak ayal praktik HD ini sangat menguntungkan bagi provider atau klinik/rumah sakit penyedia layanan HD.
Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan. Pertama, dalam dunia pelayanan kesehatan, provider atau rumah sakit atau pemilik klinik adalah agen yang menjadi penasihat sekaligus menyediakan jasa kepada pasien. Jadi, ketika pasien PGK datang ke rumah sakit dan tidak berbekal informasi tentang penyakitnya, terapi yang akan dia jalani sangat bergantung pada nasihat provider.
Meski ditanggung BPJS, klaim untuk CAPD belum masuk INA-CBG seperti HD, tetapi dengan klaim terpisah. Jadi, jika ingin menaikkan coverage CAPD, tidak mungkin tanpa melakukan intervensi sistem insentif, yaitu bagaimana supaya CAPD masuk ke skema pembayaran. Kedua, rendahnya praktik CAPD disebabkan suplai cairan CAPD yang saat ini dimonopoli satu pemasok, yaitu Baxter. Fresenius Medical Care dan Sanbe Farma sebagai pemasok cairan CAPD saat ini masih dalam proses registrasi.
Perlu Edukasi Tata Laksana Dokter dan Perawat
Sementara itu, Dr Afiatin SpPDKGH, anggota Perhimpunan Dokter Nefrologi (Pernefri) Jawa Barat, mengatakan, prevalensi penderita GGK di Jawa Barat sebelum era BPJS adalah 664 per juta penduduk. Penduduk di Jawa Barat sekitar 40 juta jiwa. Data tadi menunjukkan bahwa dibutuhkan kesiapan dalam jumlah alat HD dan perawat HD yang sangat banyak. Pada 2013, pasien CAPD di Jawa Barat hanya 2,57%.
Untuk mengurangi ketergantungan mesin HD dan perawat HD, Pernefri Jawa Barat mencoba menaikkan cakupan pasien CAPD. Idealnya, cakupan CAPD mencapai 30% agar kebutuhan mesin HD dan perawat HD mendekati ideal sehingga satu perawat hanya menangani enam pasien HD. Agar cakupan CAPD sampai 30%, maka tahap awal adalah melakukan pelatihan pada dokter penyakit dalam, dokter bedah umum, perawat, dan masyarakat, dalam hal ini kader sebagai orang terdekat pasien, untuk perawatan CAPD.
"Pemasangan alat dialisis dalam perut dilakukan dokter spesialis penyakit dalam jika tidak tersedia konsultan ginjal hipertensi atau spesialis bedah umum. Pemasangan alat CAPD dilakukan di faskes tingkat dua dan tidak perlu rumah sakit rujukan. Setelah itu, pasien dikembalikan ke daerahnya dan diawasi kader dan keluarga," tutur dr Afiatin.
Lebih jauh, kajian hasil studi yang dilakukan Pernefri merekomendasikan perlu dilakukan peningkatan cakupan CAPD di Indonesia yang saat ini baru 2%-3% dari total penderita GGK.
Komplikasi penyakit ginjal kronik tidak hanya butuh biaya perawatan mahal, tetapi juga risiko kematian tinggi. Terapi GGK meliputi transplantasi ginjal, hemodialisis (HD), dan continous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) atau sering disebut peritoneal dialisis saja. Metode peritoneal dialisis yaitu pasien melakukan cuci darah secara mandiri dan tidak perlu ke rumah sakit.
Prof Budi Hidayat, Ketua CHEPS FKMI UI, mengatakan, data antara Januari 2014-Desember 2015 menunjukkan, jumlah pasien penyakit ginjal tahap akhir mencapai lebih dari 5 juta (4,5 juta rawat jalan dan lebih dari 600.000 rawat inap). Total klaim biaya perawatan HD mencapai Rp7,6 triliun sejak awal BPJS (2014) sampai 2016. Hasil beberapa kajian menunjukkan bahwa biaya CAPD sebenarnya lebih efektif dibandingkan HD. Selain itu, kualitas hidup pasien yang menjalani CAPD umumnya lebih baik dan tidak membutuhkan klinik atau sarana khusus.
"Tetapi, faktanya berbeda. Di Indonesia, baru 2% pasien gagal ginjal yang sudah menggunakan CAPD (data tahun 2016)," ungkap Prof Budi.
Data BPJS Januari-Desember 2016 menunjukkan bahwa baru 18.597 peserta CAPD dengan total biaya Rp98,7 miliar, jauh dibandingkan pasien HD yang mencapai 3,1 juta orang dengan total biaya Rp3,1 triliun. Mengapa CAPD kurang populer?
Untuk menjawabnya dapat dilihat fenomena terapi dialisis sejak BPJS dijalankan. Salah satu respons paling signifikan dari diberlakukannya BPJS adalah berkembangnya klinik HD di seluruh Indonesia. Tak ayal praktik HD ini sangat menguntungkan bagi provider atau klinik/rumah sakit penyedia layanan HD.
Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan. Pertama, dalam dunia pelayanan kesehatan, provider atau rumah sakit atau pemilik klinik adalah agen yang menjadi penasihat sekaligus menyediakan jasa kepada pasien. Jadi, ketika pasien PGK datang ke rumah sakit dan tidak berbekal informasi tentang penyakitnya, terapi yang akan dia jalani sangat bergantung pada nasihat provider.
Meski ditanggung BPJS, klaim untuk CAPD belum masuk INA-CBG seperti HD, tetapi dengan klaim terpisah. Jadi, jika ingin menaikkan coverage CAPD, tidak mungkin tanpa melakukan intervensi sistem insentif, yaitu bagaimana supaya CAPD masuk ke skema pembayaran. Kedua, rendahnya praktik CAPD disebabkan suplai cairan CAPD yang saat ini dimonopoli satu pemasok, yaitu Baxter. Fresenius Medical Care dan Sanbe Farma sebagai pemasok cairan CAPD saat ini masih dalam proses registrasi.
Perlu Edukasi Tata Laksana Dokter dan Perawat
Sementara itu, Dr Afiatin SpPDKGH, anggota Perhimpunan Dokter Nefrologi (Pernefri) Jawa Barat, mengatakan, prevalensi penderita GGK di Jawa Barat sebelum era BPJS adalah 664 per juta penduduk. Penduduk di Jawa Barat sekitar 40 juta jiwa. Data tadi menunjukkan bahwa dibutuhkan kesiapan dalam jumlah alat HD dan perawat HD yang sangat banyak. Pada 2013, pasien CAPD di Jawa Barat hanya 2,57%.
Untuk mengurangi ketergantungan mesin HD dan perawat HD, Pernefri Jawa Barat mencoba menaikkan cakupan pasien CAPD. Idealnya, cakupan CAPD mencapai 30% agar kebutuhan mesin HD dan perawat HD mendekati ideal sehingga satu perawat hanya menangani enam pasien HD. Agar cakupan CAPD sampai 30%, maka tahap awal adalah melakukan pelatihan pada dokter penyakit dalam, dokter bedah umum, perawat, dan masyarakat, dalam hal ini kader sebagai orang terdekat pasien, untuk perawatan CAPD.
"Pemasangan alat dialisis dalam perut dilakukan dokter spesialis penyakit dalam jika tidak tersedia konsultan ginjal hipertensi atau spesialis bedah umum. Pemasangan alat CAPD dilakukan di faskes tingkat dua dan tidak perlu rumah sakit rujukan. Setelah itu, pasien dikembalikan ke daerahnya dan diawasi kader dan keluarga," tutur dr Afiatin.
Lebih jauh, kajian hasil studi yang dilakukan Pernefri merekomendasikan perlu dilakukan peningkatan cakupan CAPD di Indonesia yang saat ini baru 2%-3% dari total penderita GGK.
(amm)